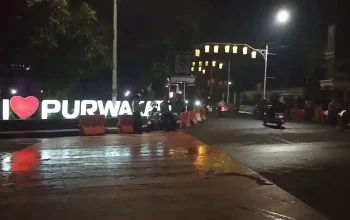Penulis : Prof. Henri Subiakto, Guru Besar Ilmu Komunikasi di Universitas Airlangga (Unair)
JABARNEWS| BANDUNG – Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menutup pintu kriminalisasi kritik. Namun negara justru membukanya kembali dari arah lain. Kamis, 2 Januari 2026, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru dan revisi KUHAP resmi berlaku. Bersamaan dengan itu, pasal penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan lembaga negara kembali hidup.
Padahal norma ini sebelumnya dicabut MK karena bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi. Kini, pasal itu hadir lagi. Lebih rapi. Lebih sistematis. Namun juga lebih berbahaya.
Masalah utamanya terletak pada frasa “menyerang kehormatan atau martabat”. Frasa ini longgar. Multitafsir. Dan mudah ditarik ke mana saja. Akibatnya, kritik bisa dipidana. Protes bisa dibungkam. Ekspresi publik bisa dianggap kejahatan.
Dari Putusan MK ke Pasal Karet Negara
Putusan MK seharusnya menjadi pagar konstitusi. Namun pagar itu kini dilangkahi oleh pembentuk undang-undang. Negara seolah berkata: apa yang dibatalkan, bisa dihidupkan kembali dengan wajah baru.
Secara substansi, larangan penghinaan ini tetap menyasar hal yang sama. Presiden dan Wakil Presiden kembali ditempatkan sebagai simbol yang “harus dilindungi” dari kritik warga. Padahal dalam demokrasi, kekuasaan justru wajib siap dikritik.
Dengan definisi yang kabur, pasal ini memberi ruang luas bagi aparat untuk menafsir sesuai selera. Terutama ketika kritik dianggap “tidak sopan”, “menyakitkan”, atau “mengganggu stabilitas”.
Di titik ini, hukum pidana berubah fungsi. Bukan lagi pelindung warga. Melainkan alat disiplin politik.
Netizen di Ujung Pidana
Ancaman tidak berhenti di elit politik. Ia turun ke level paling bawah. Ke warga biasa. Ke netizen.
KUHP Baru juga menghidupkan kembali pasal penghinaan ringan, yang dulu ada di Pasal 315 KUHP lama. Kini ia hadir sebagai Pasal 436 KUHP Baru. Konsekuensinya nyata. Ucapan kasar di ruang publik atau media sosial bisa berujung pidana hingga 6 bulan penjara atau denda Rp10 juta.
Kata-kata seperti “anjing”, “babi”, “bajingan”—yang selama ini menjadi bagian dari ekspresi emosional sehari-hari—berpotensi menyeret seseorang ke ruang tahanan.
Pasal ini dianggap multitafsir. Dan karena itu berbahaya. Ia bisa digunakan untuk kriminalisasi ekspresi, kritik spontan, bahkan kemarahan publik terhadap ketidakadilan.
Polisi Superpower dan KUHAP yang Mengkhawatirkan
Masalah tidak berhenti di KUHP. KUHAP Baru membawa persoalan lain. Lebih struktural. Lebih sistemik.
Kewenangan polisi diperluas. Mulai dari penangkapan hingga penggeledahan. Tanpa pengawasan yang kuat, kondisi ini berpotensi menjadikan aparat sebagai “superpower”.
Risikonya jelas. Abuse of power. Penegakan hukum yang makin represif. Dan perlindungan HAM yang makin tipis.
Dalam praktik, aparat sering menafsir norma “dipas-paskan” dengan kasus. Bukan untuk keadilan. Melainkan untuk kepentingan politik dan ekonomi. Akibatnya, kepastian hukum semakin menjauh.
Restorative Justice: Gagasan Baik, Aparat Lama
Pendukung KUHP dan KUHAP Baru—termasuk pemerintah dan sebagian DPR—terus menggaungkan narasi dekolonialisasi hukum. Mereka menyebut ini sebagai upaya meninggalkan warisan Belanda. Mereka juga membanggakan pasal keadilan restoratif, pemulihan korban-pelaku, serta pidana alternatif seperti kerja sosial.
Di atas kertas, gagasan ini tampak modern. Bahkan progresif.
Namun persoalannya bukan hanya pada teks undang-undang. Persoalannya ada pada aparat. Mentalitas lama masih dominan. Budaya represif belum berubah.
Sementara kesiapan aparat menerapkan pendekatan restoratif masih diragukan.
Tanpa perubahan cara pandang, pasal progresif hanya akan menjadi hiasan. Sementara pasal represif justru menjadi senjata.
Demokrasi di Tengah Overcriminalization
Kekhawatiran lain tak kalah serius. Overcriminalization mengintai. Hukum pidana masih berpotensi digunakan sebagai alat represi terhadap kelompok kritis. Aktivis. Akademisi. Jurnalis. Warga biasa.
Situasi ini diperparah oleh belum sinkronnya KUHP dan KUHAP Baru dengan aturan lain. Seperti UU ITE dan berbagai undang-undang pidana khusus. Tumpang tindih norma membuka ruang kriminalisasi berlapis.
Ironisnya, semua ini terjadi di tengah tren kemunduran demokrasi. Ruang kritik menyempit. Kebebasan berekspresi terancam. Dan hukum kembali dipakai untuk menakut-nakuti.
Karena itu, peringatan ini penting diulang. Lebih berhati-hatilah menjaga kata-kata di media sosial.
Jika UU ITE yang sudah “lebih jelas” saja masih sering ditarik-tarik, maka dengan tambahan pasal KUHP Baru, risikonya jauh lebih besar—terutama jika model penegakan hukum masih belum berubah.
Demokrasi tidak mati dalam satu malam. Ia mati perlahan. Salah satunya lewat pasal-pasal yang dulu dibatalkan, lalu dihidupkan kembali.(Red)